
Sekitar dua jam saya berbincang dengan Bapak Anwar Akib. Melihat kondisinya yang tampak lemah, saya khawatir perbincangan yang terlalu lama akan mengganggu kesehatannya. Saya pun pamit, keluar ke teras rumah, lalu duduk di lantai untuk mengenakan sepatu.
Tiba-tiba, beliau ikut duduk di samping saya, bersila di lantai. Suaranya yang bergetar berbisik, “Saya masih berharap orang daerah punya atensi lebih, karena ini masalah leluhur yang sudah diakui dunia. Jangan sampai diakui dan dibanggakan dunia, tapi terlantar di kampung sendiri.”
Saya urung mengenakan sepatu. Posisi duduk saya perbaiki, lalu bertanya untuk memperjelas, “Orang daerah maksudnya yang mana, Etta?”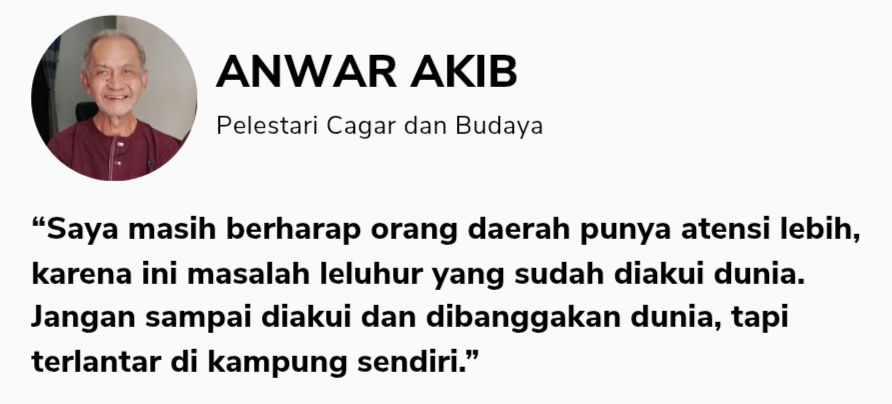
Beliau menghela napas, lalu menjawab, “Waktu itu, tidak jelas mau ke dinas mana. Yang menangani kebudayaan hanya fokus pada musik, pakaian adat, dan seni tradisional. Jadi bingung mau melapor ke mana. Padahal ini masalah arkeologi dan purbakala. Tidak sama seperti sekarang, yang sudah ada bidang khususnya.”
Saya bisa merasakan, semangat Anwar Akib untuk membicarakan kepurbakalaan di Soppeng seolah tak akan habis, meski fisiknya terbatas. Rasanya beliau ingin berkata, “Jangan dulu pulang, masih banyak yang mau saya ceritakan.” Namun, demi memperhatikan kondisinya, saya kembali berpamitan untuk kedua kalinya.
Keluar dari rumah beliau, saya melaju dengan motor menuju Makassar. Panasnya kota, debu, macet, dan keraguan saya terhadap aplikasi penunjuk arah membuat perjalanan terasa panjang. Dari arah Paccerakkang, saya berniat menuju Tamalanrea. Tapi sekitar 30 menit berlalu, saya tak kunjung sampai di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan. Rupanya jalur yang saya pilih mengarah ke Kota Maros. Tersesat. Ya sudahlah, mungkin ini memang takdir dari Yang Kuasa.
Sesat sebelum tiba di rumah, saya singgah di kios penjual es kelapa muda di depan MTos. Sambil menunggu pesanan datang, saya mencoba menghubungi kembali Kak Iwan Sumantri, peneliti senior dan arkeolog UNHAS yang kini telah purna bakti. Saya ingin mendengar pandangannya tentang Situs Calio, sekaligus harapannya ke depan.
“Situs Calio di Soppeng adalah jejak purba Lembah Walanae yang mengungkap fosil, artefak, dan sejarah manusia awal di Sulawesi. Kini, temuan itu diakui dunia lewat publikasi di jurnal Nature. Calio perlu dijaga sebagai laboratorium alam terbuka, menguatkan riset internasional sekaligus menjadi ruang edukasi dan kebanggaan budaya bagi masyarakat lokal maupun dunia,” ucapnya.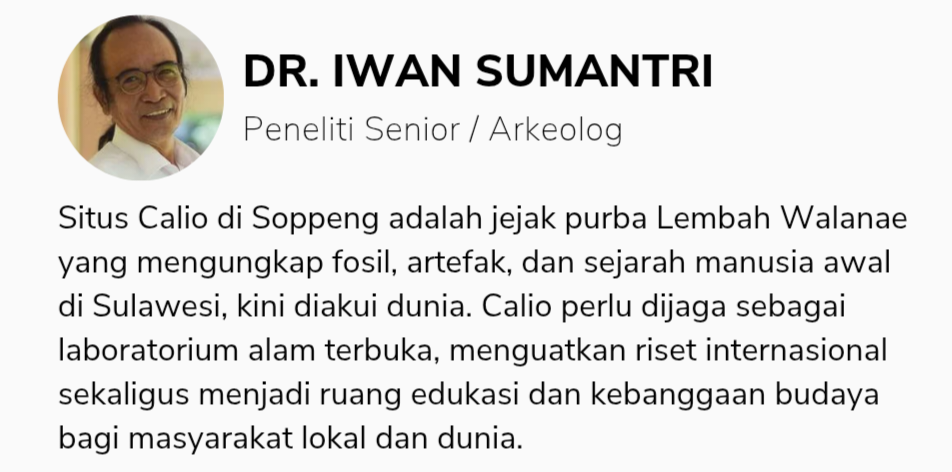
Dari ucapannya, saya menangkap maksud bahwa Calio bukan sekadar lokasi penelitian arkeologi. Ia adalah ruang belajar yang hidup, tempat pengetahuan, kebanggaan, dan identitas bertemu. Dalam pandangan Kak Iwan, Calio punya potensi menjadi “Sangiran”-nya Sulawesi, di mana sains berjalan beriringan dengan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Pesanan es kelapa muda campur gula merah tiba. Tangan kiriku mengaduk pelan, berharap kesegarannya melepas dahaga sekaligus mendinginkan kepala yang sedari tadi terpanggang terik matahari. Sambil menunggu, saya menghubungi Rustan Lebe, Pamong Budaya di Museum dan Cagar Budaya, pemerhati sekaligus pelestari situs prasejarah untuk menanyakan hal yang sama.
Menurut Rustan, jika Calio kini terasa “mendunia”, itu lebih karena wawasan kita selama ini terkurung. Faktanya, Calio dan kawasan Cabbenge telah lama dikenal di dunia arkeologi sebagai sumber penting informasi awal persebaran manusia di Asia Tenggara. Bertahun-tahun para peneliti bekerja tanpa sorotan publik, hingga akhirnya temuan ini memperkaya pengetahuan, mengangkat identitas, dan menegaskan posisi kita sejajar dengan peradaban besar lain.
Namun, ia menegaskan, penemuan ini semestinya bukan sekadar komoditas atau aset ekonomi. Lebih dari itu, ia adalah cermin atau bahkan pukulan telak di ulu ati yang mengingatkan kita bahwa nenek moyang kita pernah sejajar ritme peradabannya dengan Eropa, Tiongkok, bahkan Jawa, tetapi kita gagal menjaganya. Meski peluang ekonomi terbuka lebar, sebagai warisan budaya, situs ini wajib dikelola bijak dan terpadu dengan potensi lain di Lembah Walanae.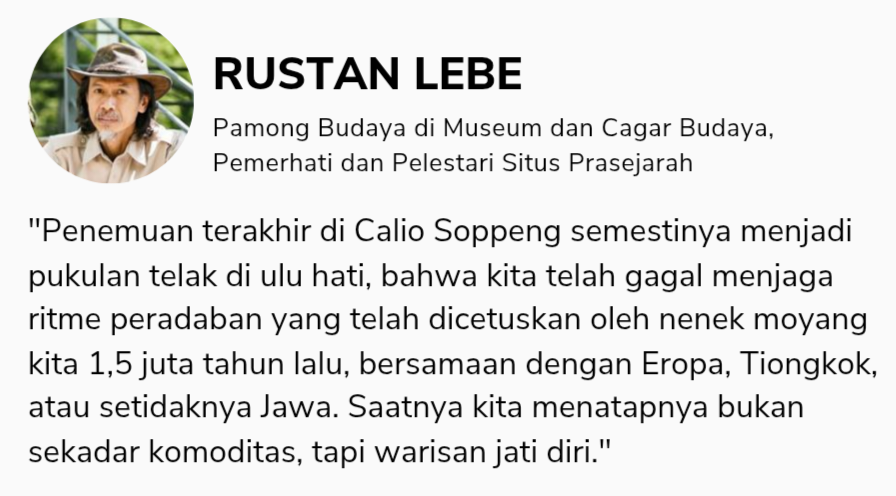
“Jangan berdiri sendiri,” tegasnya. Situs arkeologi, geologi, atau paleontologi harus menjadi bagian dari paket besar pariwisata dipadukan dengan destinasi alam maupun buatan agar semua pihak terlibat, berkontribusi, dan memanen bersama, tanpa lagi bertanya: apa yang saya dapatkan?
Pendapat Rustan Lebe membuat saya terkejut, bahkan merasa sedikit terpojok, seolah-olah ia menunjuk langsung ke arah saya. Namun, saya menyadari bahwa itu bukan semata kritik tanpa harapan.
Banyak pihak yang benar-benar berempati pada situs Calio dan kepurbakalaan di Soppeng. Kritik itu justru penuh harap agar kita semua mengambil langkah nyata, berbasis ilmu pengetahuan dan kebanggaan daerah yang tulus. Bukan sekadar bangga saat tim peneliti dan ahli datang, lalu kembali sunyi, tenggelam dalam keheningan yang panjang.
Kini, saatnya membalikkan lembaran itu. Melangkah bersama, menjaga warisan leluhur dengan kesungguhan, dan menjadikannya sumber inspirasi sekaligus kekuatan nyata bagi masa depan. Agar situs Calio tak hanya dikenal dunia, tapi juga dihidupi oleh masyarakatnya sendiri.







