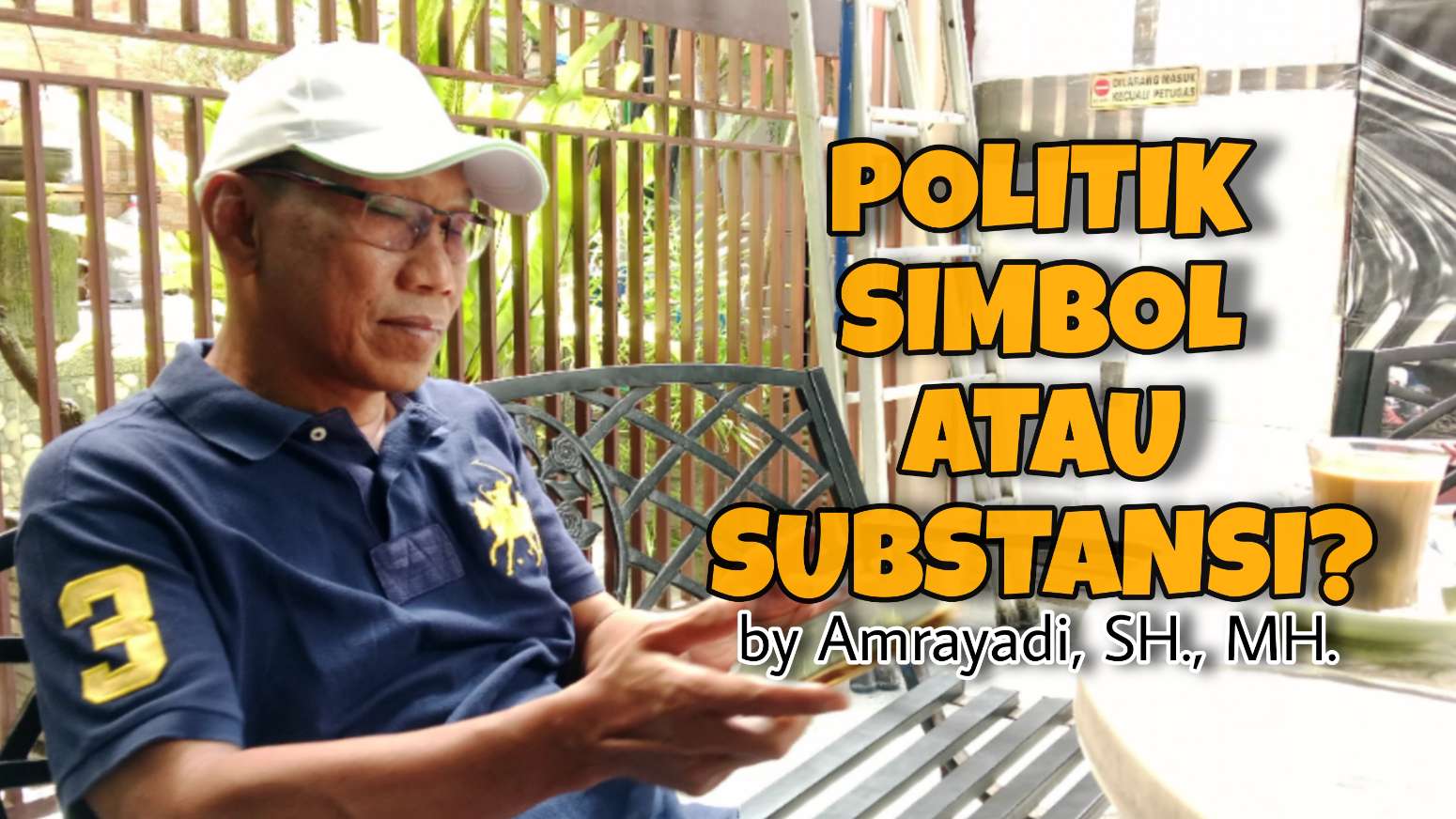Soppeng (1/9/2025). Di sebuah siang yang teduh di Kota Soppeng, aroma kopi hangat memenuhi ruang di salah satu warkop. Di meja kaca sederhana, dua cangkir kopi mengepul, satu di hadapan saya, satu lagi di depan Amrayadi SH, MH, pemerhati demokrasi sekaligus mantan Ketua KPUD Soppeng (2013–2018) dan mantan Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan (2018–2023). 
Suasana intim itu menjadi latar perbincangan serius tentang fenomena penonaktifan artis politisi di DPR RI yang ramai diperbincangkan publik.
Dengan senyum tipis, Amrayadi membuka pandangannya. Menurutnya, keputusan cepat partai menonaktifkan artis-politisi dari jabatan internal DPR bukanlah reformasi mendasar, melainkan respons simbolik. “Mereka tetap anggota DPR secara hukum, hak keuangan dan kursi tidak dicabut. Jadi ini bukan substansi, hanya sinyal bahwa partai terlihat tegas,” ujarnya sambil menyeruput kopi.
Ia menekankan, opini publik berperan besar dalam mendorong langkah itu. Kemarahan masyarakat yang dipicu video viral artis-politisi segera membentuk tekanan kolektif, sehingga partai tidak punya banyak pilihan selain bertindak cepat. “Opini publik bekerja sebagai tekanan nyata. Sanksi cepat adalah cara paling murah dan efektif untuk meredam risiko reputasi,” katanya.
Namun, bagi Amrayadi, tindakan ini mencerminkan politik sinyal (signalling politics). Partai ingin terlihat responsif, sementara substansi persoalan—kode etik, transparansi anggaran, hingga disiplin internal DPR—tetap luput dari perhatian. Ia mengingatkan, publik bisa saja merasa puas sejenak, tapi problem struktural akan tetap mengendap jika hanya artis-politisi yang dijadikan “tumbal”.
“Visibilitas mereka tinggi, media cepat menyorot. Kalau politisi non-artis melakukan hal sama, efeknya tidak sebesar ini,” ujarnya. Kalkulasi politik inilah, menurutnya, yang membuat artis-politisi lebih rentan dijadikan simbol kesalahan.
Padahal, pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan di DPR relatif terbatas. Fraksi dan mekanisme kolektif lebih dominan daripada inisiatif individu. “Mereka lebih banyak didorong sebagai figur untuk mendulang suara,” kata Amrayadi sembari mengaduk kopi dengan gerakan pelan.
Ia mengingatkan bahwa fokus publik pada artis-politisi justru berisiko menutupi isu substansi. Isu lebih besar seperti penggunaan fasilitas DPR, efisiensi anggaran, dan lemahnya pengawasan internal sering kali tenggelam. “Kalau perhatian hanya pada simbol, maka transparansi dan reformasi tidak tersentuh,” tegasnya.
Amrayadi menutup perbincangan dengan refleksi. Menurutnya, agar kepercayaan publik benar-benar pulih, DPR harus berani melangkah ke arah reformasi nyata yaitu keterbukaan anggaran, publikasi fasilitas secara rutin, audit independen, dan penegakan kode etik yang konsisten. Tanpa itu, sanksi terhadap artis-politisi hanya akan menjadi drama politik singkat, bukan solusi jangka panjang.
Di warkop itu, percakapan berakhir dengan tegukan terakhir kopi. Hening sejenak menggantung, seolah menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar, beranjak dari simbol ke substansi.