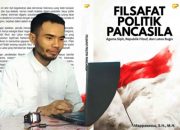ICO CABBENG: Sejarah yang Mungkin Lebih Tua dari yang Kita Pikirkan
Oleh: H.A.M. Zulkarnain, ST., MM., C.BJ., C.EJ., C. Inv.
Di relief Candi Borobudur dan Candi Sojiwan, terpahat sosok manusia tengah memegang wadah sirih dan mengunyah sesuatu. Arkeolog menyimpulkan bahwa adegan itu menggambarkan praktik nyirih, kebiasaan mengunyah sirih yang lazim di masa itu (abad ke-8 hingga ke-9 Masehi). Namun sebagian peneliti modern menafsirkan kemungkinan adanya unsur lain dalam kunyahan tersebut: tembakau[^1].
Dalam sejarah umum, tembakau baru masuk ke Nusantara sekitar awal abad ke-17, dibawa oleh bangsa Portugis, Spanyol, atau Belanda, setelah sebelumnya menyebar dari benua Amerika ke Eropa.
Lantas mungkinkah tembakau sudah dikenal masyarakat lokal jauh sebelum kolonialisme?
Di Temanggung, Jawa Tengah, hidup cerita tentang Ki Ageng Makukuhan, seorang tokoh yang diyakini sebagai perintis tembakau. Legenda lokal menyebut Ki Makukuhan memperoleh bibit tembakau dari Sunan Kudus, lalu menyebut tanaman itu sebagai “tambaku”, yang dalam bahasa Jawa lantas berubah jadi “mbako”[^2].
Cerita ini dihidupi masyarakat lereng Sumbing-Sindoro sebagai warisan turun-temurun yang lebih sakral dari sejarah tertulis.
Di Madura, muncul nama Pangeran Katandur, yang dalam bahasa lokal berarti “orang yang menanam.” Ia diyakini sebagai tokoh penyebar tembakau sejak abad ke-12, dengan nama asli Habib Ahmad Baidlowi[^3]. Tidak hanya di Madura, sejumlah komunitas adat di Nusantara seperti masyarakat Sunda Wiwitan di Ciptagelar atau Wetu Telu di Bayan juga menyimpan kepercayaan bahwa tembakau adalah tanaman warisan nenek moyang, sejajar dengan cengkeh atau pinang.
Cerita semacam itu belum ditemukan secara eksplisit di Sulawesi Selatan. Tapi di Lembah Walanae, khususnya wilayah Lilirilau di Kabupaten Soppeng, tembakau telah dikenal lama oleh masyarakat dengan nama lokal: ico. Di sana, tak ada ritual besar seperti among tebal di Jawa. Tapi proses penanaman hingga perajangan dilakukan dengan keteraturan turun-temurun.
Setiap musim kemarau, ladang-ladang di dataran keras Labae, Citta, hingga Sekkanyili berubah menjadi lahan tanam ico. Setelah dipetik, daun tembakau dijemur di pekarangan rumah dan aromanya menjadi penanda waktu di kampung.
Sejak era pendudukan Jepang, bahkan jauh sebelumnya, Ico Cabbeng disebut demikian karena warna kecoklatannya setelah dikeringkan telah menjadi komoditas perdagangan. Dikirim ke pasar-pasar Parepare, Sidrap, hingga Pinrang. Menandakan bahwa tembakau ini bukan tanaman asing. Ia sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Meskipun tidak ditemukan catatan tertulis yang pasti, satu petunjuk menarik bisa ditarik dari kehadiran Villa Yuliana, bangunan bergaya kolonial yang dibangun pada tahun 1905 oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk tempat peristirahatan bangsawan Belanda di Soppeng. Kehadiran villa tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi lokasi strategis dan cukup penting dalam pandangan penguasa kolonial. Maka tak tertutup kemungkinan, jika pun tembakau diperkenalkan oleh Belanda, maka perkenalan itu terjadi paling lambat pada era yang sama, atau bahkan sebelum Villa Yuliana dibangun.
Apalagi diketahui bahwa pada masa itu, Belanda sedang gencar mengembangkan komoditas tembakau di berbagai wilayah Hindia Timur, terutama di daerah dengan kontur dataran tinggi seperti Deli, Temanggung, dan sebagian Sulawesi. Dalam konteks itu, Lembah Walanae dengan iklim kering dan lahan pegunungan, sangat memungkinkan menjadi bagian dari jalur penyebaran tembakau.
Tentu, semua ini masih berupa dugaan. Tapi dugaan yang dilandasi jejak-jejak nyata di lapangan dan narasi sejarah yang saling berkelindan.
Kapan tepatnya ico mulai ditanam?
Tidak ada catatan resmi. Tapi sejarah tembakau nasional menyebutkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun perkebunan tembakau skala besar di Deli, Sumatera Timur pada 1860-an, dipelopori oleh J. Nienhuijs[^4]. Bahkan sebelum itu, dalam Babad Tanah Jawi dan Serat Centhini (1814), masyarakat Jawa telah digambarkan sebagai pengudut, perokok yang menghisap tembakau dalam pipa atau lintingan[^5].
Tentu kisah Ico Cabbeng di Lembah Walanae tidak akan ditemukan dalam kitab seperti Serat Centhini. Tapi bukan berarti sejarahnya tidak ada. Bisa jadi, ia hidup lewat kebiasaan. Lewat cerita di sawah. Atau mungkin dalam tembang yang tak pernah tercatat.
Kini, ketika rokok modern membanjiri pasar, sisa kejayaan Ico Cabbeng tetap hadir. Tak lagi diproduksi besar-besaran, tapi masih dibudidayakan oleh petani yang memilih bertahan. Di sela serbuan produk pabrik, mereka menyimpan aroma masa lalu yang belum selesai diceritakan.
Barangkali, sejarahnya memang tidak tertulis. Tapi seperti asap tipis yang keluar dari sebatang lintingan ico, ia tetap hidup melayang perlahan dari Lembah Walanae menuju ruang waktu yang lebih luas.
Catatan Sumber:
- [^1]: Anggraeni, Dewi. Relief Borobudur: Narasi Arkeologi dan Tafsir Budaya. Penerbit Ombak, 2012.
- [^2]: Santosa, I. B. (2014). Tembakau dan Wangi Rakyat. Jakarta: Pustaka Obor.
- [^3]: Maulana, A. (2017). “Tembakau Madura dalam Perspektif Kultural dan Ekonomi.” Jurnal Kebudayaan Tropis, Vol 3 No 1.
- [^4]: Tichelman, G.L. (1952). Tobacco in the Dutch East Indies. Jakarta: Royal Tropical Institute (KITLV).
- [^5]: Kuntowijoyo. (1991). Budaya dan Masyarakat dalam Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.